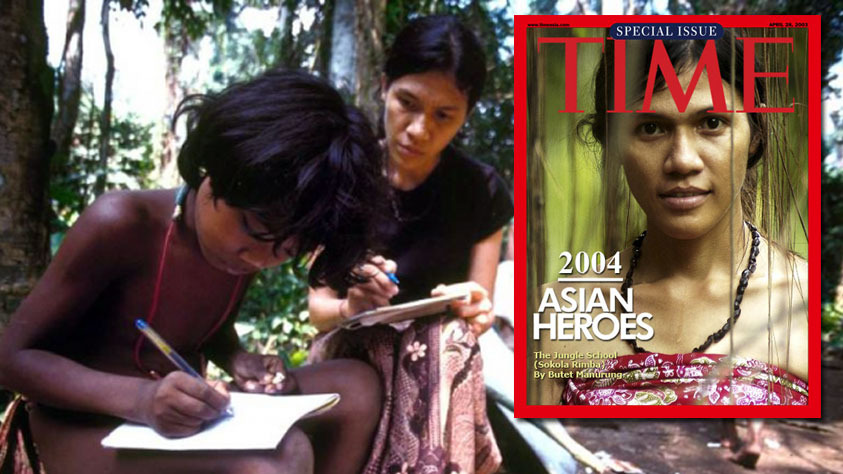Setelah mengidentifikasi tantangan internal terkait pasokan sampah, harga listrik, dan surplus daya di Indonesia (baca disini) , penting untuk melihat bagaimana negara lain mengimplementasikan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Keberhasilan atau kegagalan PSEL sangat bergantung pada konteks lokal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi insinerator semata, melainkan oleh ekosistem yang mendukungnya.
Model Ekonomi Sirkular Jepang & Denmark: PSEL sebagai Resor Terakhir
Negara-negara maju seperti Jepang dan Denmark sering disebut sebagai contoh sukses dalam waste-to-energy (WtE). Namun, kesuksesan mereka bukan karena mereka memprioritaskan pembakaran sampah, melainkan karena mereka menempatkan WtE sebagai pilihan terakhir dalam hierarki pengelolaan sampah yang sangat matang.
Di Jepang, adopsi teknologi WtE canggih seperti gasifikasi didorong oleh kondisi geografis yang ekstrem: kepadatan penduduk yang tinggi dan lahan yang sangat terbatas untuk TPA. Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi yang luar biasa, menghasilkan biaya TPA (landfill cost) tertinggi di dunia. Tingginya biaya pembuangan inilah yang membuat investasi pada teknologi WtE yang mahal menjadi layak secara ekonomi. Namun, yang lebih penting, WtE di Jepang hanya memproses sampah residu—sampah yang benar-benar tidak dapat didaur ulang atau dikomposkan. Ini dimungkinkan oleh sistem yang dibangun selama puluhan tahun, yang mencakup disiplin publik yang tinggi dalam pemilahan sampah di sumber, tingkat daur ulang yang luar biasa (misalnya, 98% untuk logam), dan kerangka kebijakan ekonomi sirkular yang kuat.
Sementara itu, di Denmark, pendekatan WtE terintegrasi secara mendalam dengan sistem energi dan agenda iklim nasional. Negara ini adalah pelopor dalam memanfaatkan sampah untuk jaringan pemanas distrik (district heating), di mana fasilitas insinerasi menyediakan sekitar 20% dari total panas untuk pemanas distrik dan 5% dari kebutuhan listrik nasional. Implementasi ini didukung oleh kebijakan fiskal yang kuat, seperti pajak TPA dan insinerasi yang tinggi yang diperkenalkan sejak tahun 1987, serta larangan total untuk menimbun sampah yang dapat dibakar. PSEL di Denmark, seperti yang dicontohkan oleh fasilitas ikonik Amager Bakke (Copenhill) di Kopenhagen, adalah bagian dari solusi sistemik yang lebih besar yang memprioritaskan ekonomi sirkular, bukan solusi tunggal yang berdiri sendiri.
Pelajaran dari Jepang dan Denmark: mereka terlebih dahulu membangun fondasi yang kokoh—disiplin publik, infrastruktur pemilahan, insentif ekonomi (pajak TPA yang tinggi), dan pola pikir ekonomi sirkular. Baru setelah itu mereka menerapkan teknologi WtE yang canggih untuk menangani sisa sampah yang sudah terpilah dan bernilai kalor tinggi.

India dan Thailand: Peringatan yang Diabaikan
Negara berkembang seperti India dan Thailand menawarkan sebuah cermin peringatan bagi Indonesia. Negara-negara ini, yang memiliki karakteristik sampah dan tantangan sosial-ekonomi yang mirip dengan Indonesia, menunjukkan risiko dari penerapan solusi PSEL secara prematur.
India adalah studi kasus kegagalan yang paling relevan. Banyak pabrik WtE di India gagal beroperasi secara efisien atau bahkan bangkrut karena dihadapkan pada masalah yang sama persis dengan yang dihadapi Indonesia: sampah kota yang tidak terpilah, memiliki kadar air sangat tinggi (hingga 50%), dan nilai kalor yang rendah. Upaya membakar sampah jenis ini tidak hanya tidak efisien secara energi tetapi juga menghasilkan emisi polutan beracun (dioksin, furan) dan abu terbang (fly ash) yang berbahaya dalam jumlah besar, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di sekitar pabrik. Lemahnya penegakan peraturan dan standar emisi yang longgar memperburuk masalah ini—risiko yang juga sangat nyata di Indonesia. India hanya mampu menghasilkan sekitar 10% energi dari keseluruhan kapasitas potensial PSELnya.
Thailand juga berjuang dengan masalah sampah plastik dan infrastruktur yang tidak memadai, meskipun telah memiliki peta jalan pengelolaan sampah nasional. Tantangan utamanya, yang sangat mirip dengan Indonesia, adalah kurangnya pemilahan sampah yang efektif di tingkat rumah tangga dan ketergantungan yang besar pada sektor informal untuk daur ulang. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dari atas ke bawah (top-down) tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan investasi masif pada infrastruktur dasar pengumpulan dan pemilahan serta edukasi publik yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, strategi Indonesia saat ini tampaknya lebih condong ke model kegagalan yang terlihat di negara-negara berkembang sejawatnya daripada model keberhasilan di negara maju. Indonesia mencoba mengimpor teknologi “hilir” untuk menyelesaikan masalah yang terletak di “hulu”. Tanpa membangun sistem pengelolaan sampah yang matang dari hulu, proyek PSEL berisiko tinggi menjadi fasilitas yang tidak efisien, merugi secara finansial, dan berbahaya bagi lingkungan—persis seperti yang terjadi di India.
Dengan mempertimbangkan risiko dan pelajaran dari negara lain, artikel terakhir akan membahas strategi untuk mengubah tantangan ini menjadi peluang sukses.