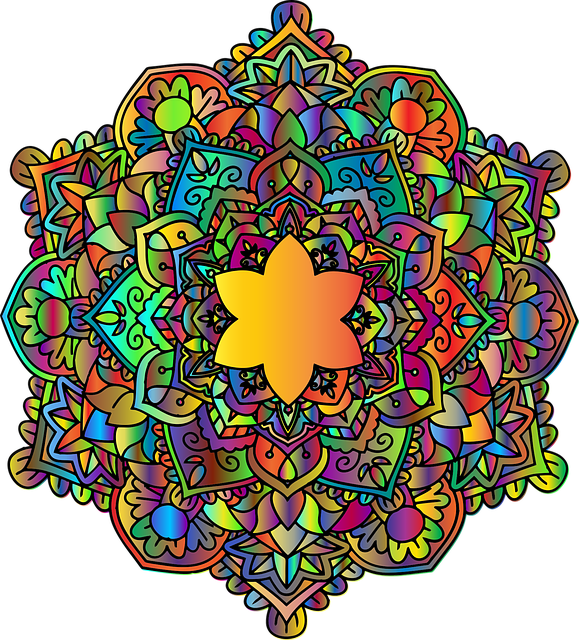Dilema Ganda di Persimpangan Jalan Sampah dan Energi
Indonesia berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, negara ini menghadapi krisis pengelolaan sampah perkotaan yang tak terbantahkan, sebuah “darurat sampah” yang ditandai dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang meluap dan sistem pengelolaan yang tidak memadai. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta ton, dengan komposisi didominasi oleh sampah organik (sisa makanan) dan sampah plastik. Dari total timbulan sampah tersebut, baru sekitar 39,01% yang berhasil dikelola, sementara sisanya masih belum terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan. Dalam konteks inilah, program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) diposisikan sebagai salah satu solusi andalan. Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, berupaya untuk mempercepat pembangunan fasilitas PSEL, dengan tujuan ambisius untuk mencapai target 100% sampah terkelola pada tahun 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Perpres 109/2025, yang merupakan revisi dari Perpres 35/2018, dirancang untuk mengatasi hambatan investasi yang selama ini menghantui proyek PSEL. Regulasi ini menawarkan serangkaian insentif yang sangat menarik bagi investor, termasuk harga jual listrik yang tinggi dan jaminan kontrak jangka panjang. Namun, di balik niat baik untuk menyelesaikan masalah sampah, kebijakan ini melahirkan sebuah dilema. Analisis menunjukkan bahwa kerangka kebijakan PSEL saat ini, meskipun berhasil menarik minat investasi, berpotensi menciptakan tiga tantangan baru yang jauh lebih sistemik dan berbahaya dalam jangka panjang. Pertama, keberlanjutan pasokan sampah sebagai bahan bakar (feedstock) masih diragukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedua, penetapan tarif listrik yang tinggi menciptakan distorsi ekonomi yang parah, membebani keuangan negara, dan menempatkan PT PLN (Persero) dalam posisi sulit. Ketiga, penambahan kapasitas listrik dari PSEL bertentangan secara strategis dengan kondisi surplus daya yang telah terjadi di sistem kelistrikan utama, khususnya Jawa-Bali.

Foto: 22Kartika, CC BY-SA 3.0
Karpet Merah bagi Investor, Beban bagi Negara?
Perpres 109/2025 bukan sekadar pembaruan kebijakan, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental model bisnis PSEL di Indonesia. Jika Perpres 35/2018 sebelumnya dianggap kurang berhasil menarik investasi, regulasi baru ini secara sistematis menghilangkan hampir semua risiko yang dihadapi oleh pengembang swasta dan pemerintah daerah, lalu mentransfernya secara kolektif ke pundak BUMN kelistrikan, PT PLN (Persero), dan pada akhirnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan paling signifikan adalah penetapan harga pembelian tenaga listrik oleh PLN sebesar USD 0,20 per kWh untuk semua kapasitas. Angka ini naik drastis, sekitar 48%, dari tarif tertinggi sebelumnya yaitu USD 0,1335 per kwh untuk listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo, Solo dan PLTSa Benowo, Surabaya. Melalui aturan ini maka pemerintah menghilangkan risiko pasar dan risiko harga sepenuhnya bagi investor.
Dalam skema sebelumnya, pemerintah daerah (Pemda) dibebani kewajiban membayar Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) atau tipping fee, yang seringkali menjadi kendala karena keterbatasan APBD. Perpres 109/2025 secara cerdik memindahkan beban ini. Tipping fee kini diserap oleh PLN sebagai bagian dari biaya pembelian listrik yang mahal, yang kemudian akan dikompensasi oleh pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini membebaskan Pemda dari tanggung jawab fiskal langsung, namun secara efektif menyembunyikan biaya pengelolaan sampah di dalam tagihan kompensasi energi nasional.
Perpres baru ini menetapkan durasi kontrak jual beli listrik (PJBL) atau Power Purchase Agreement (PPA) selama 30 tahun sejak proyek beroperasi secara komersial. Jaminan pendapatan selama tiga dekade ini memberikan kepastian finansial yang luar biasa bagi investor dan lembaga pemberi pinjaman. Namun, bagi negara, ini berarti terkunci dalam kontrak pembelian energi berbiaya tinggi untuk waktu yang sangat lama, menciptakan liabilitas jangka panjang yang kaku dan menghambat adopsi teknologi yang lebih baru atau lebih efisien di masa depan.
Rangkaian insentif tidak berhenti di situ. Pemda diwajibkan menyediakan lahan untuk PSEL melalui mekanisme pinjam pakai tanpa biaya sewa. PLN diwajibkan menandatangani PJBL dalam waktu sangat singkat, yaitu paling lama 10 hari kerja setelah pengembang memenuhi perizinan. Lebih jauh lagi, pengembang PSEL dibebaskan dari penalti atau denda apabila besaran daya yang dijanjikan dalam PJBL tidak terpenuhi. Kombinasi dari semua ketentuan ini menciptakan lingkungan investasi yang nyaris tanpa risiko, di mana negara menanggung hampir semua risiko—mulai dari risiko pasokan, harga, lahan, hingga kinerja operasional.
Perubahan drastis dalam alokasi risiko ini mengubah natur proyek PSEL. Dari yang semula merupakan proyek infrastruktur layanan publik (pengelolaan sampah) dengan produk sampingan energi, kini ia bertransformasi menjadi aset finansial yang dijamin negara. Produk utama yang dijual bukanlah jasa pengelolaan sampah, melainkan kontrak energi jangka panjang dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan baru ini disambut positif oleh para pelaku usaha, namun pada saat yang sama, memicu kekhawatiran serius mengenai implikasi fiskal jangka panjangnya bagi negara.
Pada artikel berikutnya, saya akan membahas tiga tantangan mendasar yang membuat fondasi operasional dan ekonomi PSEL menjadi rapuh: masalah suplai sampah, harga listrik, dan surplus daya.