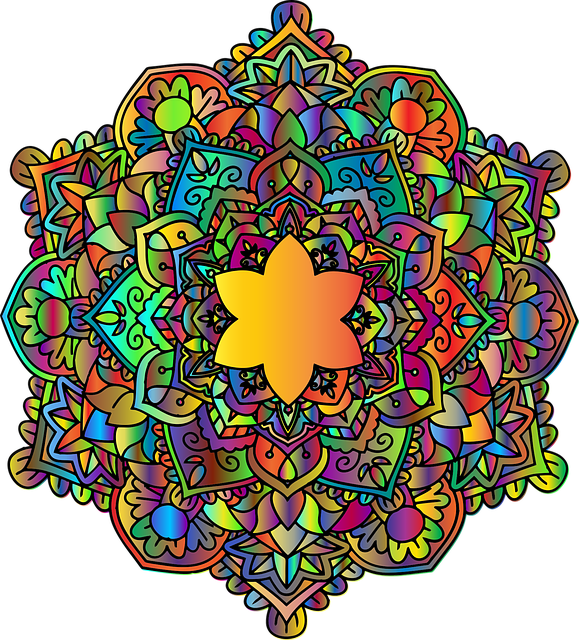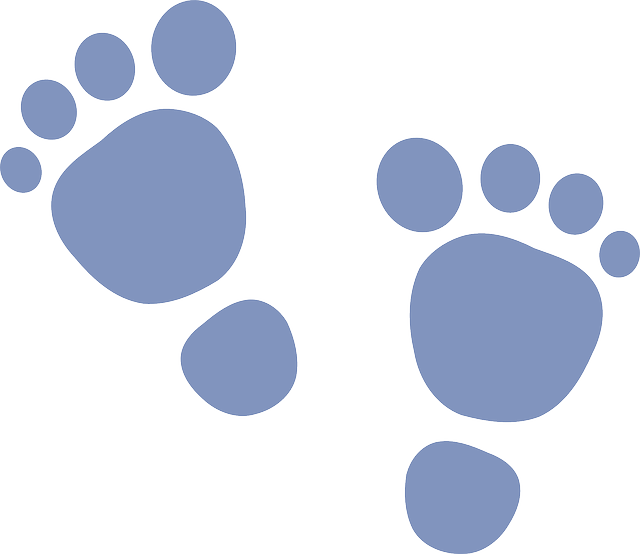Novel “Aimuna dan Sobori” karya Hanna Rambe adalah sebuah karya yang menyoroti kehidupan masyarakat Nusantara Timur dalam periode sejarah yang penuh gejolak, yaitu pada masa monopoli rempah oleh VOC. Dengan latar waktu yang diambil pasca Genosida Banda, Hanna Rambe membawa kita kembali ke sebuah era di mana pembantaian dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen telah mengakibatkan kematian ribuan rakyat Banda, sementara ribuan lainnya diperbudak dan terusir dari pulau mereka sendiri. Kejadian memilukan ini membuat warga Nusantara Timur hidup dalam ketakutan dan tercerai-berai.
Salah satu aspek menarik dari novel ini adalah penggambaran Hanna Rambe tentang bagaimana VOC melakukan monopoli rempah-rempah. Kerajaan-kerajaan yang telah takluk menerima bayaran tahunan sebagai imbalan dari mereka memberikan Hak Ekstirpasi kepada VOC. Hak ini memungkinkan VOC untuk menghancurkan kebun-kebun cengkeh, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam oleh penduduk. Tujuannya adalah menjaga agar persediaan di pasar dunia tetap rendah sehingga dapat mempertahankan harga tinggi. VOC membangun benteng dan menempatkan pasukannya di Kepulauan Rempah.

Penduduk tak kehilangan akal. Diam-diam mereka menanam cengkeh di pedalaman nun jauh, kalau perlu di lereng bukit yang tak terjangkau dari pantai. Lokasinya di pulau lain. Waktu panen, mereka jual kepada pihak lain yang bersahabat, menukar dengan barang-barang yang diperlukan rakyat setempat. Secara rutin, VOC melakukan patroli untuk mencegah segala bentuk transaksi antara warga pribumi dengan pelayar asing serta menghancurkan desa atau kelompok yang berupaya menanam rempah-rempah secara sembunyi-sembunyi.
Aimuna dan Sobori menjadi korban dari Pemusnahan Desa yang menanam rempah-rempah secara sembunyi-sembunyi. Desa mereka dimusnahkan ketika mereka baru menginjak remaja. Bersama Gamati – Kakeknya, yang lolos untuk kedua kalinya dari pembantaian. Hidup sebagai pelarian tentu tidak mudah. Mereka berusaha membangun dan menata kembali hidup mereka. Cita-cita mereka sederhana, bisa bertahan hidup dan menanam kembali cengkeh tanpa harus terganggu oleh Monopoli VOC.
Novel ini memberikan wawasan penting tentang sejarah Indonesia yang sering diabaikan dan hanya menjadi bahan hapalan dalam pelajaran sejarah maupun tes wawasan kebangsaan (TWK). Novel ini juga memberikan gambaran bagaimana ramainya kepulauan rempah. Pelayar dari berbagai belahan Bumi tumpah berebut rempah-rempah. Transaksi tukar-menukar barang beserta kuantitas dan kualitas yang diperlukan untuk mendapatkan cengkeh memberikan gambaran seberapa penting cengkeh di masa itu.
Penulis cukup baik menggambarkan kehidupan di Kepulauan rempah. Adat dan Kebiasaan warga digambarkan dengan cukup detail. Penulis menggunakan bahasa lokal dalam beberapa dialog, sehingga memberikan warna dan kedalaman pada interaksi antar karakter. Hanya saja ini berimbas pada catatan kaki yang lumayan banyak. Salah satu serpihan budaya yang menarik dalam buku ini adalah sasi—pita atau tali berwarna merah yang dipasang di batang pohon atau tiang di laut. Sasi berfungsi sebagai penanda bahwa barang-barang di tempat tersebut tidak boleh diambil tanpa izin pemiliknya, dengan risiko bagi pencuri menjadi bisu sementara dan tidak dapat pergi dari lokasi tersebut sebelum bertemu pemiliknya.
Namun, novel ini tidak lepas dari kelemahan. Beberapa penjelasan terasa diulang-ulang, seperti definisi Hongi dan Hak Ekstirpasi, yang muncul beberapa kali sepanjang buku. Pengulangan ini kadang membuat narasi terasa stagnan, padahal pembaca mungkin sudah memahami konsep tersebut di penjelasan awal. Selain itu, kesedihan yang dialami Gamati, salah satu karakter utama, juga sering diulang, sehingga bisa mengurangi dampak emosional yang diharapkan dari ekspresi perasaan tersebut. Meskipun demikian, kekurangan-kekurangan ini tidak sepenuhnya mengurangi kekuatan novel ini.